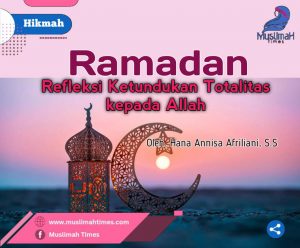Oleh. Kholda Najiyah
(Founder Salehah Institute)
Muslimahtimes.com–Apa kabar para lajang? Pasti sudah kenyang dengan pertanyaan, “Kapan nikah?” Apalagi di momen Lebaran saat bersilaturahim ke tetangga dan kerabat. Berat memang, saat status belum juga berubah. Masih sendiri, belum memperkenalkan (calon) pasangan.
Di luar kuasa Allah atas belum ketemunya jodoh, persoalan lajang yang belum menikah ini perlu perhatian. Pasalnya, jumlah lajang yang menunda menikah semakin banyak. Terbukti dengan turunnya angka pernikahan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, angka pernikahan pada 2023 mencapai titik terendah selama lebih dari seperempat abad ini, sejak 1996/1997. Hanya ada 1.577.255 pasangan menikah atau turun 128.093 dibanding 2022 yang sebanyak 1.705.348.
Sementara, tren bercerai meningkat terus selama periode yang sama. Jika 1996/1997 ‘hanya’ ada 114.252 pasangan yang bercerai, BPS mencatat, pada 2023 terdapat 463.654 kasus. Tampaknya, pernikahan kini tak lagi dianggap sakral.
Dahulu, pasangan suami istri sangat menjunjung tinggi pernikahan sehingga berjuang mati-matian mempertahankannya. Rumah tangga pun awet sampai maut memisahkan. Sekarang, konflik sedikit saja langsung cerai. Lihatlah, usia pernikahan baru seumur jagung sudah bubar. Apakah fenomena ini berpengaruh terhadap enggannya para lajang untuk menikah?
Pergeseran Nilai
Dewasa ini muncul fenomena Waithood, yang didefinisikan sebagai masa penantian anak muda menuju jenjang kemapanan, terutama secara finansial. Masa-masa membangun karier, di mana para pemuda dan pemudi harus menghasilkan uang banyak agar siap menikah dan membangun finansial untuk masa tua.
Waithood diperkenalkan oleh Profesor Siane Singerman dari American University pada 2007. Berdasarkan risetnya, ditemukan bahwa generasi muda di Timur Tengah menunda untuk menikah karena kondisi finansial yang belum baik. Marcia Inhorn dari Yale University dalam risetnya, mendukung teori tersebut. Ia menemukan, generasi muda mayoritas menunda pernikahan, terutama perempuan dan kaum berpendidikan.
Hal ini tidak terlepas dari terjadinya pergeseran nilai-nilai yang dianut generasi di era sekuler liberal yang serba materialistis ini. Perubahan nilai-nilai itu antara lain:
Pertama, nilai materi telah mendominasi. Generasi muda saat ini sangat fokus menjadikan materi sebagai sumber kebahagiaan, sehingga tidak siap jika menikah dalam kondisi sederhana. Tidak siap hidup bersahaja. Ibaratnya, tidak siap berjuang pascanikah. Maunya serba mapan. Berbeda dengan generasi terdahulu yang menikah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Namun, mereka berjuang dari nol bersama-sama.
Saat ini, para lajang sibuk memperkaya diri dengan bekerja dan berkarier sebagus mungkin. Mengumpulkan harta entah sampai kapan, karena nilainya tergerus inflasi hingga kemapanan tak juga terbeli. Menabung terus, tapi tak juga berani melamar anak orang, karena merasa tidak pernah cukup. Tidak percaya diri, minder dan cemas untuk membangun rumah tangga.
Sementara lajang perempuan, juga sibuk berkarier demi mengumpulkan harta. Pikir mereka, memuaskan diri sendiri dulu. Cari duit untuk membayar mimpi-mimpinya akan kebendaan yang selama ini tidak ia dapatkan dari orang tuanya.
Baik impian tentang fesyen, perawatan diri, traveling maupun pendidikan tingkat lanjut. Akibatnya, para lajang perempuan tidak memikirkan menikah, sebelum terwujud semua yang ia impikan.
Kedua, nilai keluarga telah luntur. Generasi muda saat ini menganggap berkeluarga sebagai beban. Bagi laki-laki, menikah berarti kelak mereka harus membiayai istri dan anak-anaknya. Bahkan, siap menanggung mertua atau bahkan ipar secara ekonomi.
Sedangkan dalam pandangan perempuan, pernikahan berarti akan mengganti prioritas utamanya untuk suami, dan anak-anak. Kelak tidak akan bisa menyenangkan diri sendiri, oleh karena itu puas-puasin dulu selama masih melajang.
Ketiga, nilai religius bahwa menikah adalah ibadah, telah tergerus. Generasi muda tidak lagi menjadikan pernikahan sebagai ibadah, yang berdimensi pahala di dalamnya. Jika pandangan bahwa menikah adalah ibadah tertancap kuat, seharusnya para lajang berlomba-lomba menjalani pernikahan. Nyatanya tidak.
Menikah hanya dipandang sebagai pergantian status. Hanya berkomitmen dalam dimensi dunia saja, yakni meraih kemanfaatan seperti ekonomi, perasaan dicintai dan disayangi.
Keempat, nilai budaya yang sudah tidak rigit. Saat ini, fenomena lajang yang belum menikah semakin umum terjadi. Masyarakat tak lagi sinis atas keberadaan mereka. Tidak lagi mempermasalahkan dan menggunjingkannya. Para lajang semakin hidup nyaman dan damai, tanpa peduli dengan statusnya, karena tak lagi dikejar pertanyaan-pertanyaan tentang kapan menikah.
Kelima, nilai sosial, di mana pergaulan laki-laki dan perempuan semakin bebas dan terbuka. Laki-laki bisa bergaul dengan perempuan manapun yang ia suka. Tata pergaulan yang liberal, bahkan menyebabkan mereka memilih zina.
Tanpa pernikahan, kebutuhan biologis pun telah dapat disalurkan, baik dengan suka rela bersama pasangan maupun membeli jasa pemuas syahwat. Na’udzubillahi mindzalik. Ini menyebabkan minat untuk menikah semakin tipis.
Sementara itu, generasi masa kini juga menolak cara-cara perjodohan seperti zaman dulu. Terbukanya informasi, menyebabkan mereka berusaha mencari dan menelusuri sendiri pasangan yang ia idam-idamkan.
Sayangnya, semakin terbuka informasi itu, semakin menjauhkan diri dari minat untuk menikah, karena kekhawatiran dan kegalauan yang tidak beralasan. Seperti takut menikah dengan orang yang salah. Takut dikhianati atau diselingkuhi. Takut dipoligami dan sebagainya.
Dampak Sosial Jangka Panjang
Fenomena Waithood jika dibiarkan tanpa intervensi negara, bisa merugikan. Dalam jangka panjang, beban generasi akan semakin berat. Sebagai ilustrasi, jika pasangan menikah usianya semakin tinggi, berarti kesempatan untuk reproduksi semakin pendek.
Jika memiliki anak di usia semakin lanjut, kelak saat anak-anak remaja dan masih butuh biaya untuk kuliah, orang tua sudah masuk fase pensiun dan tidak mampu lagi bekerja. Orang tua bahkan bisa jadi malah menjadi beban anak-anaknya, sementara anaknya belum mampu mandiri.
Kondisi tersebut, akan semakin sulit untuk memutus rantai generasi sandwich. Individu terus mendapatkan tekanan hidup dari generasi sebelumnya, sekaligus beban dari generasi yang dilahirkannya. Jika ia menjadi seorang suami atau ayah, ia harus menanggung biaya orang tua sekaligus anak-anaknya.
Bagi negara, beban akan dirasakan dengan banyaknya proporsi penduduk usia tua dibanding usia produktif. Sebab, para lajang yang beranjak menua dan tidak menikah, kelak akan menambah daftar lansia yang perlu disantuni. Mengingat, tidak ada yang menanggung hidupnya, kecuali ia sudah memiliki cukup dana pensiun mandiri.
Fenomena Global
Menurunnya angka pernikahan dan tingginya Waithood tidak hanya di Indonesia. Di negeri-negeri maju bahkan sudah terjadi lebih dahulu, hingga mengakibatkan rendahnya angka pernikahan, anjloknya angka kelahiran dan tingginya penduduk usia lansia.
Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem sekuler kapitalis. Sistem ini membiarkan individu bebas sebebas-bebasnya, hingga tidak ada harapan untuk bergantung pada negara. Termasuk dalam menyelesaikan masalah lajang mereka.
Bagaimanapun, para lajang yang ingin menikah, seharusnya difasilitasi dan didukung oleh negara. Bagaimana mekanismenya? Para pemuda harus mendapat bekal yang proporsional dan benar tentang dunia pernikahan. Masukkan dalam kurikulum pendidikan.
Para pemuda wajib militer, disiapkan untuk menjadi suami dan ayah. Harus punya kemampuan dasar mencari nafkah dan memimpin. Pemuda yang tidak mampu, disubsidi untuk menikah. Dengan demikian, tidak ada kecemasan untuk membangun keluarga.
Sedangkan para pemudi, juga tidak akan ragu menerima lamaran mereka, karena tahu kualitasnya. Mereka juga disiapkan untuk menjadi istri dan ibu pengatur rumah tangga. Dibekali skill dasar yang berkaitan dengan tugas pokoknya kelak, sehingga tidak cemas akan kemampuannya memperjuangkan kebahagiaan dalam pernikahan.
Negara bisa mempermudah dan bahkan memfasilitasi perjodohan, dengan memanfaatkan data base kependudukan yang mutakhir. Di situ akan tertera jumlah penduduk produktif dan statusnya, sehingga dengan mudah para pencari jodoh menemukan calon pasangannya.
Negara wajib melarang keras pacaran, menghukum zina dan menghapuskan berbagai media perangsang syahwat di ranah publik, sehingga satu-satunya pintu untuk memenuhi kebutuhan biologis hanyalah melalui pintu pernikahan. Dengan demikian para pemuda dan pemudi tidak punya pilihan lain selain menikah.
Adapun untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga, hingga pintu perceraian tak diminati, negara harus membuka fasilitas konseling seluas-luasnya tanpa biaya. Memastikan setiap pernikahan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Memastikan setiap pernikahan tidak ada kekerasan dan kezaliman.
Tentu saja, negara seperti itu bukan model negara sekuler. Sebab, menciptakan kondisi seperti itu butuh suasana keimanan dan ketakwaan dari tiga pihak, yaitu individu, masyarakat dan negara. Jika ketiganya menggunakan pilar iman dan takwa, yaitu selalu berpedoman pada syariat Allah Swt, barulah terwujud tujuan pernikahan untuk ibadah. Karena itu, persoalan Waithood ini bukan sekadar fenomena individual, tetapi sistemis yang harus diatasi secara sistemis pula.(*)